Ketika Adab Bertemu Algoritma: Drama Trans7, Santri, dan Kita Semua
Loading views...
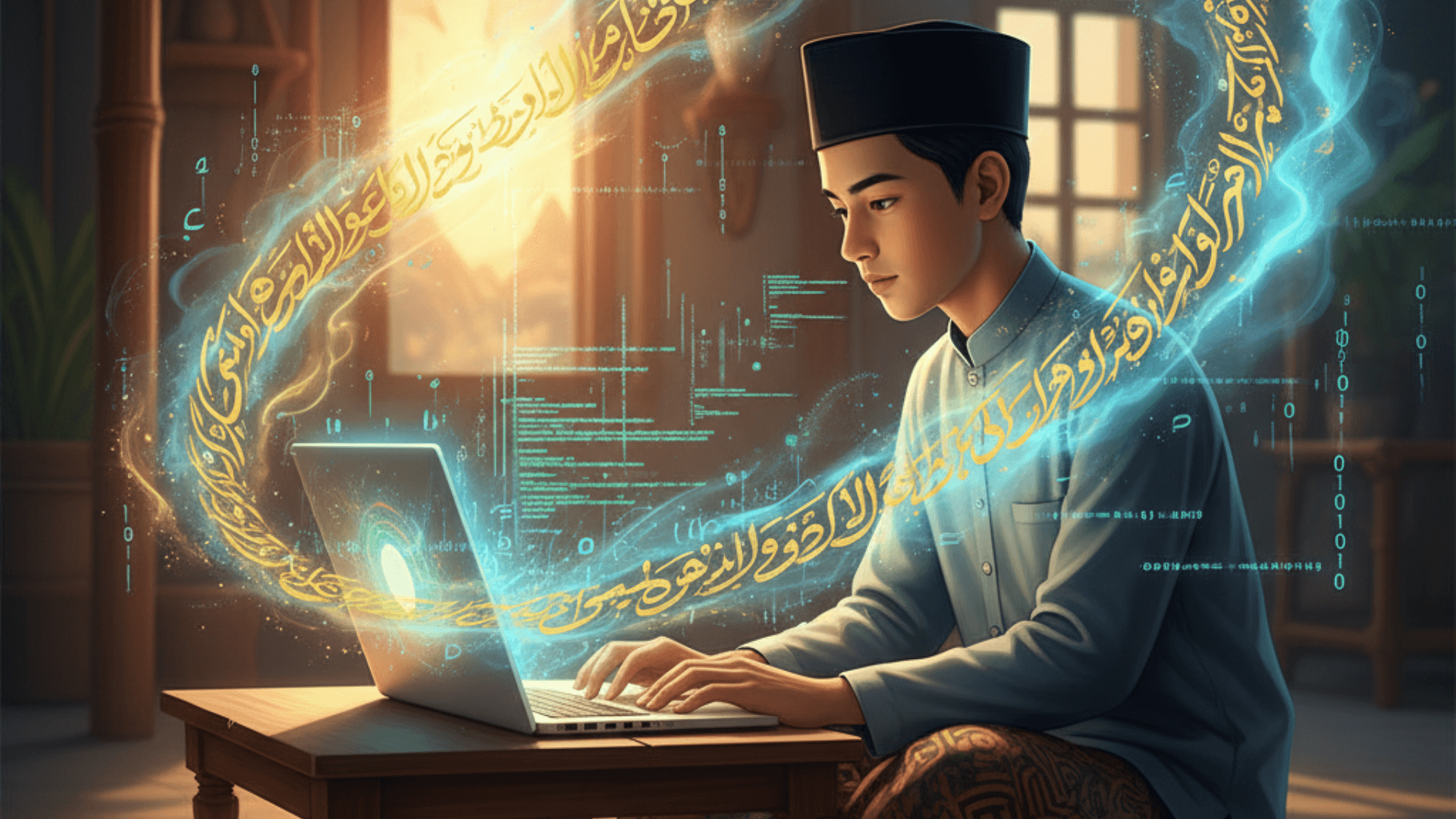
Ilustrasi: pertemuan antara adab dan algoritma — dunia pesantren dan teknologi digital.
Beberapa minggu terakhir, dunia maya Indonesia terasa panas. Bukan karena gosip selebriti atau debat politik, melainkan karena sebuah tayangan di Trans7 yang dianggap menyinggung dunia pesantren. Tayangan itu menampilkan kehidupan santri dan kiai dengan cara yang, menurut banyak kalangan, terkesan merendahkan. Dari situlah gelombang kekecewaan muncul. Santri, alumni pesantren, dan masyarakat yang memiliki kedekatan dengan kultur pesantren merasa tersinggung.
Protes pun merebak di berbagai daerah. Santri turun ke jalan, sebagian melakukan aksi di depan kantor Trans7, sebagian lain di depan gerai Transmart. Aksi terakhir inilah yang kemudian menjadi sorotan—karena sebagian publik menilai “salah alamat.” Tapi di balik kehebohan itu, ada hal yang jauh lebih menarik untuk dibedah: kenapa bisa terjadi ketegangan sebesar ini antara media modern dan tradisi pesantren yang selama ini dikenal penuh adab?
Trans7: Lupa bahwa Kecepatan Tak Selalu Sejalan dengan Kearifan
Secara objektif, Trans7 memang melakukan kesalahan profesional. Mereka menayangkan konten yang tidak sensitif terhadap nilai dan simbol dalam kultur pesantren. Santri dan kiai ditampilkan dengan cara yang mungkin “menarik secara visual”, tetapi mengabaikan konteks maknanya. Di dunia pesantren, cara berjalan, berbicara, dan berinteraksi dengan kiai bukan sekadar gestur, tapi simbol penghormatan yang punya nilai spiritual.
Namun, perlu juga diakui: kesalahan itu tampaknya bukan karena niat jahat, melainkan karena kelalaian. Di ruang redaksi modern, tekanan untuk membuat konten cepat, viral, dan memancing emosi sering mengalahkan kebutuhan untuk memahami konteks sosial. Dalam ekonomi atensi seperti sekarang, yang penting bukan seberapa dalam maknanya, tapi seberapa tinggi klik dan view-nya.
Di titik inilah, media sering lupa bahwa mereka bukan hanya mesin berita, tapi juga pembentuk kesadaran publik. Trans7 mungkin tak berniat menyinggung siapa pun, tapi ketidakhati-hatian mereka membuktikan bahwa kecerdasan produksi tanpa kepekaan budaya bisa melahirkan bencana sosial.
Pesantren: Marah Itu Wajar, Tapi Strategi Harus Naik Level
Dari sisi pesantren, kemarahan itu sah. Dunia pesantren adalah ruang yang dijaga dengan kehormatan dan nilai-nilai spiritual. Ketika dunia itu digambarkan secara salah, tentu wajar jika muncul reaksi keras. Ini bukan sekadar soal harga diri, tapi soal simbol dan martabat.
Namun, perlu juga diakui bahwa sebagian aksi protes tampak tidak terarah. Demonstrasi di depan Transmart, misalnya, memang punya alasan simbolik—karena Transmart dan Trans7 berada di bawah induk perusahaan yang sama. Tapi bagi masyarakat umum, hal itu tampak seperti salah sasaran. Akibatnya, pesan moral yang ingin disampaikan jadi teralihkan oleh kehebohan lokasi.
Pesantren selalu identik dengan adab dan kebijaksanaan. Maka ketika marah pun, publik berharap kemarahan itu tetap beradab. Tidak harus lembek, tapi cerdas. Boleh keras, tapi tepat sasaran. Karena di era media sosial, pesan bisa tenggelam bukan karena salah isi, tapi karena salah cara menyampaikannya.
Algoritma: Dalang Sunyi yang Mengatur Emosi Kita
Tapi ada aktor lain yang sering terlupakan dalam drama ini: algoritma. Begitu potongan video itu viral, mesin-mesin platform digital langsung bekerja. Konten yang paling marah, paling panas, dan paling emosional otomatis muncul di beranda kita. Semakin banyak orang marah, semakin tinggi engagement, dan semakin besar pula keuntungan bagi platform.
Dengan kata lain, kemarahan publik bukan hanya hasil spontan dari kekecewaan, tapi juga produk dari sistem digital yang memang didesain untuk memancing emosi. Kita dikondisikan untuk cepat bereaksi, tapi lambat memahami. Akhirnya, isu yang seharusnya jadi pelajaran etika berubah jadi tontonan kemarahan massal.
Dan di situlah bahayanya: ketika rasa hormat terhadap budaya dan kesabaran dalam berpikir kalah oleh sistem yang mengejar viralitas. Di titik ini, Trans7 bukan satu-satunya yang salah; kita semua ikut berperan dalam memperkuat budaya buru-buru marah.
Dua Dunia yang Sebenarnya Bisa Bersinergi
Kalau mau jujur, media dan pesantren sebenarnya bisa saling belajar. Trans7 bisa belajar tentang kepekaan moral dan kedalaman makna dari pesantren. Sebaliknya, pesantren bisa belajar tentang strategi komunikasi dan cara mengelola opini publik dari media.
Bayangkan jika keduanya berkolaborasi. Trans7 bikin program edukatif yang menampilkan kehidupan pesantren dengan gaya modern dan inspiratif. Santri diundang jadi pembicara, bukan sekadar objek liputan. Sebaliknya, pesantren mengajarkan literasi digital kepada santri, agar mereka bisa menjadi kreator konten yang santun tapi tetap relevan dengan zaman.
Dengan begitu, dunia adab dan dunia algoritma tidak perlu terus berseberangan. Mereka bisa berdampingan, saling menjaga agar kebenaran tidak kehilangan empati dan kebebasan tidak kehilangan batas.
Pelajaran Buat Kita Semua
Kasus ini bukan hanya soal Trans7 atau pesantren. Ini soal bagaimana kita sebagai bangsa menghadapi era di mana kecepatan informasi sering mengalahkan kedalaman makna. Kita sering salah paham karena menilai dari potongan video, bukan dari keseluruhan konteks. Kita sering terprovokasi oleh narasi emosional, bukan fakta substansial.
Padahal, baik media maupun pesantren sejatinya punya misi yang sama: mendidik. Bedanya hanya alat—yang satu lewat kamera, yang satu lewat kitab. Tapi esensinya tetap: menuntun masyarakat agar berpikir, beradab, dan berempati.
Penutup: Saatnya Adab dan Algoritma Berdamai
Kisah Trans7 dan pesantren ini bisa jadi pelajaran besar bagi kita semua. Media perlu belajar bahwa kebebasan berekspresi harus jalan beriringan dengan kepekaan budaya. Pesantren perlu menyadari bahwa menjaga martabat juga bisa dilakukan lewat strategi komunikasi yang elegan dan cerdas.
Kita hidup di zaman di mana yang viral sering dianggap benar, dan yang tenang sering dianggap kalah. Padahal, kekuatan sejati ada pada keseimbangan: ketika adab bertemu algoritma.
Karena kalau media terus kehilangan adab, ia akan kehilangan arah. Dan kalau pesantren terus kehilangan strategi, ia akan kehilangan pengaruh. Tapi jika keduanya saling memahami, Indonesia akan punya sesuatu yang lebih berharga dari sekadar viralitas—yakni kebijaksanaan yang hidup di tengah hiruk-pikuk data.